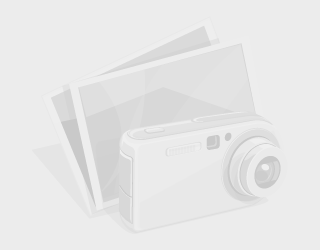”Bangsa yang besar yaitu bangsa yang mau dan bisa menghargai sejarah usaha para penberlalu dan silamnya”. Dalam konteks ini, sudahkan kita sebagai bangsa yang besar? Benarkah kita sebagai bangsa sudah sangat perhatian dan menghargai para pendekar pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan tanah air, masyarakat dan Negara Indonesia? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kitapun menjadi ragu dan termangu, apakah kita sudah termasuk bangsa yang menghargai sejarah usaha para pendekar kita sendiri, mengingat di antara kita banyak yang tidak memahami sejarah usaha bangsa. Indikator yang terlihat salah satunya banyak anggota masyarakat dan para remaja kita yang tidak senang, tidak berminat dengan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah di sekolah menjadi mata pelajaran yang tidak menarik dan membosankan. Pelajaran sejarah dipandang menjadi pelajaran yang tidak penting, apalagi tidak di UN-kan. Posisi mata pelajaran di sekolah dipandang sebagai mata pelajaran pemanis yang sanggup dibelajarkan oleh siapa saja. Mengapa demikian? Slaha satu sebabnya sanggup ditebak lantaran pembelajaran sejarah kita cenderung hafalan dan kurang berarti dalam kehidupan keseharian, yang berada di tengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif-materialistik. Hal ihwal termasuk mata didik yang tidak terkait eksklusif dengan soal bahan dan ekonomi, tidak begitu diminati.
Pembelajaran sejarah bergotong-royong tidak sekedar mentasumsi pertanyaan what to teach, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu dilangsungkan biar sanggup menangkap dan menanamkan evaluasi serta mentransformasikan pesan di balik realitas sejarah itu kepada penerima didik. Proses pembelajaran ini tidak sekedar penerima didik menguasai bahan ajar, tetapi diperlukan sanggup membantu pematangan kepribadian penerima didik sehingga bisa merespon dan mengikuti keadaan dengan perkembangan sosio kebangsaan yang semakin kompleks serta tuntutan global yang semakin kencang.
Kehidupan bangsa Indonesia remaja ini ternyata belum ibarat yang dicita-citakan. Peristiwa politik tahun 1998 yang telah mengakhiri kekuasaan Orde Baru dengan banyak sekali euforianya ternyata menyisakan luka mendalam di banyak sekali aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai bentuk pelanggaran masih terus terjadi. Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM, sikap amoral dan runtuhnya budi pekerti luhur, anarkhisme dan ketidaksabaran, ketidakjujuran dan budaya nerabas, rentannya kemandirian dan jati diri bangsa, terus menghiasai kehidupan bangsa kita. Semangat kebangsaan, jiwa kepahlawanan, rela berkorban, saling bergotong royong di kalangan masyarakat kita mulai menurun. Kita ibarat telah kehilangan abjad yang selama beratus-ratus tahun bahkan berabad-abad kita bangun. Pada kondisi yang ibarat ini nampaknya pada moment peringatah “Hari Pahlawan” kali ini menjadi menarik untuk mencoba kembali menelaah kaitan antara pembelajaran sejarah dengan penilaian-penilaian kepahlawanan.
MAKNA PEMBELAJARAN SEJARAH
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran sejarah bergotong-royong mempunyai arti yang strategis. Pembelajaran sejarah yaitu suatu proses untuk membantu berbagi potensi dan kepribadian penerima didik melalui pesan-pesan sejarah biar menjadi warga bangsa yang bakir dan bermartabat. Sejarah dalam hal ini merupakan totalitas dari acara insan di masa lampau (Walsh, 1967), dan sifatnya dinamis. Maksudnya, bahwa masa lampau itu bukan sesuatu final, tetapi bersifat terbuka dan terus berkesinambungan dengan masa kini dan yang akan datang. Karena itu sejarah sanggup diartikan sebagai ilmu yang meneliti dan mengkaji secara sistematis dari keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau dengan segala aspek kejadiannya, untuk kemudian sanggup memmemberikankan pepenilaianan sebagai pedoman penentuan keadaan sekarang, serta cermin untuk masa yang akan datang.
Ludang keringh jauh pengertian sejarah juga berkait dengan kasus kemanusiaan dan sebuah teater di mana insan menjadi pemain watak, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sudah ada. Sejarah akan mendidik insan untuk memahami “sangkan paran “ dan eksistensi dirinya (Soedjatmoko, 1986) sehingga sanggup memperkuat bukti diri diri dan bukti diri nasional, atau bukti diri sebagai suatu bangsa. Dalam kaitan ini maka pembelajaran sejarah berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah yaitu suatu orientasi intelektual, dan suatu sikap jiwa untuk memahami eksistensi dirinya sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai suatu bangsa (Soedjatmoko, 1986). Taufik Abdullah (1974) menegaskan bahwa kesadaran sejarah tidak lain yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri sanggup diartii sadar akan eksistensi dirinya sebagai individu, sebagai makhluk sosial termasuk sadar sebagai bangsa dan sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Sardiman A.M., 2005). Dalam konteks ini pada diri insan bergotong-royong ada dua dimensi, yakni dimensi kekhalifahan dan dimensi kehambaan.
Dengan pemahaman tersebut, pembelajaran sejarah dituntut paling tidak sanggup mengaktualisasikan dua hal yakni: (1) pendidikan dan pembelajaran intelektual, (2) pendidikan dan pembelajaran moral bangsa, civil society yang demokratis dan bertanggungtasumsi kepada masa depan bangsa (Djoko Suryo, 1991). Hal yang pertama menuntut pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan faktual, namun dituntut untuk memmemberikankan latihan berfikir kritis, bisa menarik kesimpulan, memahami arti dari suatu insiden sejarah berdasarkan kaidah dan norma keilmuan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana, penting untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sejarah. Sementara itu hal yang kedua menunjuk pada pembelajaran sejarah yang berorientasi pada pendidikan kemanusiaan yang memperhatikan penilaian-penilaian luhur, norma-norma, dan aspek kemanusiaan lainnya.
Dengan berbagi dua hal : pendidikan intelektual dan pendidikan moral atau pendidikan kemanusiaan, maka arah pembelajaran sejarah diperlukan sanggup mencapai tujuan yang menopang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran sejarah akan sanggup melandasi pendidikan kecerdasan intelektual, sekaligus ikut mendasari pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan penuh amarah bahkan kecerdasan spiritual dalam rangka meningkatkan martabat insan Indonesia. Dalam pengaplikasian di sekolah, tujuan pembelajaran sejarah tersebut terkait dengan adanya tujuan yang dikenal dengan istilah instructional effects dan tujuan yang “mengikuti” atau tujuan ludang keringh lanjut yang disebut nurturant effects (uraian sekomplitnya lih.dalam Sardiman AM.,2005). Mencermati rumusan tersebut, nampak terang bahwa di samping aspek kognitif, dimensi afektif menpeduli porsi yang cukup penting dalam tujuan pembelajaran sejarah. Namun dalam kenyataannya timbul kritik bahwa pendidikan kita cenderung intelektualistik dan ludang keringh banyak bersifat kognitif.
Begitu juga dalam pembelajaran sejarah masih cukup memprihatinkan. Pembelajaran sejarah ludang keringh banyak hafalan dan bersifat kognitif. Akibatnya pembelajaran sejarah tidak bisa menjangkau kepada aspek-aspek moralitas, menyangkut kecerdasan penuh amarah dan spiritual. Pembelajaran sejarah kita masih jarang yang bisa memasuki wilayah ranah afektif, ibarat sikap arif, menumbuhkan semangat kebangsaan, besar hati terhadap bangsa dan negerinya, apalagi hingga memahami hakikat dirinya sebagai manifestasi kesadaran sejarah yang paling tinggi, sehingga memunculkan sikap dan tindakan sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang dan pendekar kita.
MEMBANGUN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN.
Pembelajaran sejarah, akan berbagi acara penerima didik untuk melaksanakan telaah banyak sekali peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan kepada dirinya sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak. Dari sekian insiden itu antara lain pula ada pesan-pesan yang terkait dengan evaluasi penilaian kepahlawanan ibarat keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme dan patriotisme (lih. Kabul Budiyono, 2007). Beberapa evaluasi ini sanggup digali dan dikembangkan melalui pembelajaran sejarah yang berarti . Untuk itu memang sangat dituntut adanya kreativitas dari para guru sejarah. Para guru sejarah harus menggali dan bisa mentransformasikan penilaian-penilaian tersebut kepada penerima didik.
Di dalam pelajaran sejarah banyak pokok bahasan atau topik-topik yang mengandung penilaian-penilaian kesejarahan tersebut. Misalnya kadab sedang membahas periode penjajahan, sangat tepat untuk mengaktualisasikan kembali penilaian-penilaian jati diri dan hak-hak individu atau hak-hak asasi manusia, penilaian-penilaian kemanusiaan, penilaian-penilaian nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana perlawanan yang dilancarkan oleh Sultan Agung, oleh Pangeran Diponegara, oleh Cut Nyak Dhien. Tokoh-tokoh ini berjuang tanpa pamrih demi kebebasan tanah tumpah darahnya, demi membela rakyat yang menderita akhir kekejaman kaum penjajah. Harta, jiwa dan raga dipertaruhkan demi tegaknya harga diri dan kedaulatan sebagai bangsa Berbagai bentuk usaha ini secara dikotomis sanggup diaktualisasikan penilaian-penilaian kemerdekaa. “ Kemerekaan ialah hak segala bangsa, oleh lantaran itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Satu kalimat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini secara kreatif sanggup dibahas satu atau dua kali pertemuan. Para penerima didik diajak untuk memahami dan menghayati penilaian-penilaian kemerdekaan diri, penilaian-penilaian perikemanusiaan dan evaluasi keadilan untuk kemudian menjadi kepingan dari sikap dan perilakunya. Dalam hal ini guru dituntut untuk bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada penerima didik biar meresapi bahwa tindakan kaum penjajah di bumi Nusantara sangat bertentangan dengan penilaian-penilaian kemanusiaan dan penilaian-penilaian keabuktian sebagai hak-hak asasi manusia. Hak-hak individu yang paling asasi dirampas. Tidak ada kebebasan berserikat, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan memeluk agama secara utuh. Padahal Tuhan membuat setiap bangsa, setiap insan anggota masyarakat dalam keadaan sama, kecuali lantaran kadar keimanannnya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling tepat dengan kedudukan mulia yakni sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi yang bertugas membangun dunia demi kemaslahatan tiruana orang. Kaprikornus penjajahan sangat terang bertentangan dengan fitrah dan ciptaan Tuhan. Membahas topik-topikpada periode penjajahan ini, penerima didik juga sanggup diajak untuk menghayati dan menumbukan sikap patriotisme, sikap dan tindakan anti penjajahan. Harus diyakinkan kepada penerima didik bahwa tindak penajajahan itu yaitu sikap dholim lantaran menyengsarakan rakyat banyak. Dalam konteks ini sanggup diaktualisasikan konsep jihad, “dan barang siapa berjihad di jalan Tuhan, nirwana yaitu pahalanya.”
Pembahasan topik-topik yang berkenaan dengan periode pergerakan nasional, guru perlu menekankan penilaian-penilaian nasionalisme, persatuan dan kesatuan di antara pluralisme atau keanekaragaman, toleransi dan saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa dan golongan. Tuhan telah membuat ini tiruana sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa diciptakan-Nya insan bersuku-suku dan golongan-golongan biar kita saling mengenal dan menjalin tali silaturakhim. Kalau sudah demikian maka dengan didorongkan oleh keinginan luhur yakni harapan ingin merdeka, maka terwujudlah persatuan dan kebersamaan. Usaha untuk mewujudkan persatuan ini berhasil dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa: Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol kebersamaan dalam keanekaragaman dan sekaligus memmemberikankan semangat untuk menggalang persatuan demi terwujudnya harapan kemerdekaan. Sumpah Pemuda yaitu ujud nyata dari silaturakhim nasional, “dan barang siapa yang mau menghidup-hidupkan silaturakhim maka akan dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya.” Inilah konsep nasionalisme yang dibimbing oleh penilaian-penilaian moral, penilaian-penilaian keagaaman yang oleh Toynbee dikatakan sebagai nasionalisme yang dibimbing oleh penilaian-penilaian universal agama-agama atas (higher religions) (lih. A. Syafii Maarif, 1989). Nasionalisme yang tidak dibimbing oleh penilaian-penilaian moral keagamaan, sanggup terjebak pada dua kecenderungan. Pertama, nasionalisme yang sekuler, ekstrim berludang keringhan yang sanggup melahirkan chauvinisme. Bentuk nasionalisme inilah yang dikritik oleh Toynbee, dikarenakan telah mengakibatkan berkobarnya PD II yang menghancukan peradaban manusia. Kedua, nasionalisme yang lemah sehingga menimbulkan pendukungnya tidak mempunyai pujian nasional dan jati diri bangsa. Yang kedua ini sangat bersahabat kaitannya dengan model pembelajaran yang hanya kognitif. Guru secara kreatif sanggup membahas bahan ini, contohnya dengan topik “Telaah Teks Sumpah Pemuda”
Selanjutnya untuk membahas topik-topik yang terkait dengan bahan didik pada periode kemerdekaan, guru sanggup mengaktualisasikan dan menanamkan penilaian-penilaian esensial yang relevan kepada para penerima didik, ibarat penilaian-penilaian kemedekaan, kemandirian dan kebebasan yang bertanggung tasumsi, patriotisme, kasus kepemimpinan dan keteladanan, yang telah dipertunjukkan oleh para pejuang dan pendekar nasional kita. Agar ludang keringh menumbuhkan kesadaran dan merangsang emosi penerima didik, guru sebagai fasilitator dan motivator sanggup membelajarkan penerima didik untuk menelaah biografi tokoh pejuang atau pendekar tertentu, misal Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sultan Hamengku Buwono IX untuk mendapat penilaian-penilaian kejuangan, kepemimpinan dan keteladanan.
Pembelajaran topik-topik dan penilaian-penilaian pada periode kemerdekaan itu akan ludang keringh “dahsyat” (sangat berarti), apabila guru secara kreatif mau memmemberikan sentuhan dan atau memakai perspektif spiritualisme atau penilaian-penilaian moral. (Uraian di atas bergotong-royong sudah banyak disinggung). Contoh ilustrasi wacana kemerdekaan. Kemerdekaan yaitu hak segala bangsa. Kemerdekaan fitrah dan hak asasi insan sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu masuk akal kalau bangsa Indonesia berusaha dengan segala daya, dengan penuh pengorbanan baik jiwa, raga maupun harta. Dengan semboyan “merdeka atau mati” dan disertai dengan semangat jihad, bangsa Indonesia akan berjuang hingga titik darah penghadapat n untuk sebuah kemerdekaan. Hal ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang sangat asasi dan tahapan sangat penting bagi eksistensi suatu bangsa.
PENUTUP
Demikian beberapa ilustrasi bagaimana berbagi bahan dan melaksanakan pembelajaran sejarah untuk menghidupkan penilaian-penilaian kejuangan dan kepahlawanan. Banyak bahan pembelajaran yang sanggup dimanfaatkan untuk membangun penilaian-penilaian kepahlawanan itu. Tentu hal ini sangat menuntut keberanian dan kreativitas guru. Guru perlu merubah pembelajaran sejarah yang kognitif menjadi pembelajaran yang ludang keringh berarti, kontekstual, dan menyentuh aspek-aspek afektif atau kecerdasan penuh amarah, serta kecerdasan spiritual. Pembelajaran sejarah yang bersifat kognitif hanya akan melahirkan kepuasan dengan durasi sesaat, sebaliknya pembelajaran sejarah yang bisa melatih kecerdasan penuh amarah dan spiritual, akan melahirkan kesadaran sejarah yang sejati, dan sanggup mengaplikasikan penilaian-penilaian kejuangan dari para pendekar bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syafii Maarif, (1989). “Menggugat Toynbee”, dalam Eksponen, edisi 5 Maret 1989. Juga lihat Ahmad Syafii Maarif (1985), Al Qur’an : Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi), Bandung: Pustaka.
Djoko Suryo(1996). “Pengembangan Kajian Sejarah dalam Kurikulum SLTA” Makalah, disampaikan pada program seminar dalam rangka Dies Natalis IKIP Semarang, 13 Maret 1991.
Kabul Budiyono, (2007). Nilai-penilaian Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia, Bandung : Alfabeta.
Sardiman AM. (2005). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar . Jakarta: Rajawali Pers.
Soedjatmoko (1986). Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Jakarta: LP3ES
Taufik Abdullah (1974). “Masalah Sejarah Daerah dan Kesadaran Sejarah”, Bulletin Yaperna No. 2 tahun I, Jakarta: hal. 10.
Walsh, W.H. (1967). Philosophy of History : An Introduction. New York: Harper and Row Publisher.
Advertisement